NEWS
Farhat Abbas : Menerawang Prospektus Amandemen

Jarrakpos.com. Tujuh partai politik (parpol) koalisi sudah dikumpulkan oleh Presiden. Arah lobinya jelas: amandemen. Publik meraba, amandemen yang mana? Terkait haluan negara (HN) dan hanya itu, atau akan melabar? Jika melebar, maka, amandemen terkait HN hanyalah pintu masuk untuk menggapai target politik yang jauh lebih ditarget, yakni mengamandemen Pasal 7 UUD NRI tentang masa jabatan presiden-wakil presiden. Agar masa jabatan presiden-wakil presiden menjadi tiga periode.
Muncul renungan mendasar, jika memang arahnya ke HN, apakah harus mengundang ketujuh parpol itu? Sementara, sejauh ini Jokowi hanya menyampaikan apresiasi terhadap keinginan atau upaya menghadirkan rumusan HN, tidak sampai ke level sikap (perintah untuk serius menindaklanjuti). Body language Jokowi semakin cenderung menyatakan “tidak” jika konsekuensi perumusan HN berkonsekuensi pada penataan lembaga negara (MPR) untuk dikembalikan posisinya seperti sebelum amandemen ketiga. Bahkan, kian tidak berminat, jika konsepsi HN harus disertai pertanggungjawaban presiden terkait kinerjanya, sehingga posisi presiden terancam: impeachment jika tidak confirm kinerjanya seperti yang terjadi pada Soekarno dan Gus Dur.
Karena itu, pemanggilan atau mengumpulkan ketujuh parpol tersebut dapat dibaca dengan jelas: agenda terselubung di luar persoalan HN. Menurut bocoran yang terpublikasi luas, pengumpulan ketujuh parpol itu lebih terkait agenda utama perpanjangan masa jabatan presiden: menambah satu periode lagi, bukan hanya dua periode sesuai Pasal 7 UUD NRI 1945 pasca amandemen pertama. Sebuah renungan, pastikah pengumpulan ketujuh partai koalisi itu (PDIP, Golkar, PPP, PKB, Gerindra, Nasdem dan PAN yang baru merapat ke kekausaan) akan memenuhi kepentingan pragmatis sang presiden?
Untuk menjawabnya, kita perlu menengok jumlah kursi ketujuh parpol itu di MPR. Ketujuh parpol tersebut berjumlah 471 kursi. Dengan mengacu Pasal 37 UUD NRI 1945 sebagai syarat sah mengajukan amandemen, minimal 1/3 dari 711 anggota MPR (575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD RI) atau sama dengan 237 anggota yang menyetujui usulan, maka praktis sudah terpegang kartu persetujuan pengusulan itu. Tinggal “melegalisasi” usulan perubahan itu.
Selanjutnya, usulan itu bisa tercapai persetujuan amandemen jika 2/3 anggota MPR (474 anggota) menyetujuinya. Dengan “mengantongi” suara koalisi tersebut, maka pratis tinggal mencari suara tambahan: 3 suara. Yang dibidik tentu dari DPD RI. Kita dapat membaca dengan jernih, sangatlah mungkin untuk mendapatkan suara tambahan dari unsur DPD. Dengan kata lain, sangatlah tidak mungkin untuk mengunci suara DPD agar konsisten dan berseberangan dengan keinginan Presiden.
Jika pendekatan analisisnya matematika murni, maka langkah amandemen itu bukan hanya memenuhi prasyarat prosedural sebagai mekanisme yang sah menurut konstitusi. Tapi, juga berpotensi besar tergapainya persetujuan amandemen kelima tentang perpenjangan masa jebatan presiden, dari maksimal hanya dua periode, menjadi tiga periode.
Dalam perspektif konstitusi, amandemen apapun – selagi persyaratannya terpenuhi seperti yang tertuang dalam Pasal 37 UUD NRI itu – merupakan keniscayaan, terkategori konstitusional dan sah, meski berlawanan dengan kemungkinan besar kehendak nurani mayoritas rakyat. Meski, mereka yang di parlemen merupakan representasi rakyat dan daerah, namun belum tentu sama persis dengan kepentingan mereka yang diwakilinya. Karenanya, apa yang bergulir di tengah Senayan hanyalah artikulasi kepentingan para elitis, bukan elemen seluruh anak negeri ini.
Sebuah analisis historis yang perlu kita paparkan, andai sketsa politik di parlemen itu benar-benar terjadi, maka amandemen Pasal 7 UUD 1945 tersebut merupakan pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi yang digulirkan pada 1998. Fakta sejarah mencatat, salah satu spirit atau keterpanggilan nasional yang melibatkan berbagai elemen bangsa saat reformasi adalah masalah pembatasan masa jabatan presiden, yang disepakati maksimal dua periode. Spirit reformasi inilah yang menggerakkan MPR – pada Sidang Umum MPR 14-21 Oktober 1999 – melakukan amandemen pertama dengan merubah Pasal 7 UUD NRI, di samping pasal-pasal lainnya: Pasal 5, 13, 15, 17, 20 dan Pasal 21.
Dengan demikian, amandemen kelima yang mengubah masa jabatan presiden tiga periode dan atau penambahan masa jabatan tiga tahun dalam satu periode, hal ini sama dengan mengulangi perilaku kekuasaan yang dulu (zaman Orde Baru) dibenci. Atau – secara sarkatik – bisa dikatakan, sesungguhnya rezim ini sedang memcopy paste Orde Baru. Kekuasaan – akhirnya harus diakui – memang empuk, harus dipertahankan, meski titik akhirnya harus dikoreksi secara revolusif.
Sekali lagi, apakah pengundangan ketujuh parpol tersebut pasti akan menghasilkan format konstitusi baru yang melegalkan perpanjangan masa jabatan tiga periode bagi presiden-wakil presiden? Sangat diragukan. Dalam hal ini kita perlu mempertegas kepentingan pragmatis di antara ketujuh partai koalisi itu.
Yang pertama, PDIP (128 suara) dan Gerindra (78 suara). Kedua parpol pengusung yang bertotal 206 suara ini jelas-jelas telah menunjukkan keinginan politik praktisnya. Kedua parpol ini sama-sama menunjukkan tekadnya untuk mempersiapkan kadernya untuk memimpin negeri ini pasca Jokowi berakhir kekuasaannya. Hal ini dapat kita cermati jelas pada persiapan dan bahkan sosialisasi intensif-ekstensif untuk sebuah misi utama: menggadang kader terbaiknya sebagai presiden RI ke delapan.
Yang perlu kita garis-bawahi, dengan reaksi kontra PDIP-Gerindra, minimal, dari sisi persyaratan usulan sudah terkurang 206 suara. Andai Golkar, PPP, PKB, NasDem dan PAN tetap solid mendukung gerakan amandemen Pasal 7 itu, maka jumlah pengusul amandemen tinggal 265. Memang masih bisa mengajukan usulan perubahan. Tapi, untuk mendapatkan persetujuan hasil amandemen perlu menambah dukungan 209 saura. Salah satu opsinya hanya melirik DPD. Andai DPD totally support dan itupun suatu ketidakmungkinan, hal ini pun belum mencukupi ketentuan minimal.
Konfigurasi politik tersebut berpotensi mengubah peta politik koalisi. PKB – sebagai analisis kedua – PKB yang demikian jelas telah menunjukkan ambisi politiknya untuk posisi RI-1, minimal RI-2, kian mempertegas politik mufarraqahnya (sayonara) dari koalisi pro Jokowi. Sementara, NasDem – meski lebih memilih kandidat yang prospekif untuk kemenangan pilpres – semakin jelas juga tekad mufarraqah politiknya. Sinyalnya – seperti yang sering kita saksikan selama ini — lebih mengarah ke Gubernur DKI Jakarta sekarang.
Senada dengan NasDem, Golkar pun akan melirik peluang pilpres. Ketika dirasa kalah kompetitif untuk posisi calon presiden, partai besar kedua ini akan siap digandeng dengan capres lain. Sikap politik ini mempertegas politiknya: tidak akan mendukung gerakan amandemen yang berfokus pada perpanjangan masa jabatan presiden-wakil presiden.
Perubahan konfigurasi politik ini akan melinglungkan sikap politik PPP dan PAN. Kedua parpol yang sangat dipertanyakan capaian suaranya pada perhelatan pemilihan legislatif mendatang karena bayang-bayang ketidaksampaian mencapai ambang batas parlemen 4%, hal ini menjadikan kedua parpol lebih menunjukkan sikap politik “sendiko dawuh” (ikut saja apa kata the boss), sembari merapat ke figur capres potensial. Dan PPP – sedari awal – sudah menunjukkan sinyal ke mana arah politiknya. Intinya, siap merapat ke kandidat presiden yang berpotensi menang. Sangat pragmatis.
Dari analisis konfigurasi politik tersebut, prospektus amandemen terkait Pasal 7 UUD NRI 1945 sangat suram hasilnya. Muncul renungan, bagaimana jika rezim ini ngotot, lalu obral dana ribuan trilyun? Untuk PDIP dan Gerindra kemungkinan sangat kecil menerima politik kooptasi fulusiyyah. Keduanya, menanti lima tahun lagi pasca 2024 merupakan rentang waktu yang demikian lama. Sangat mungkin, kedua parpol itu berpikir usia. Meski Puan Maharani relatif tergolong muda, tapi posisi dukungan total PDIP sangat tergatung pada keberadaan orangtuanya yang kini masih berstatus sebagai Ketua Umum PDIP. Sebuah pertanyaan mendasar, adakah jaminan Mba Mega masih ada dan cukup powerful untuk kendalikan partainya? Tak ada jaminan. Karena itu, now or never, adalah sikap politik yang jauh lebih realistis bagi kader PDIP. Sementara, Gerindra dengan kader utama Prabowo yang sudah semakin sepuh menjadi semakin buram untuk menanti penantian kepemimpinan 2029. Karena itu, 2024 adalah masa penantian yang tak bisa ditawar dan tak boleh terlepas lagi. Karena itu, siraman ribuan trilyun rupiah, sangat boleh jadi, tidak membuat dirinya silau.
Namun demikian, politik transaksional memungkinkan para komprador Jokowi tetap memaksakan kehendaknya, melalui perpanjangan masa jabatan Jokowi. Jika hal ini yang terjadi, berarti – secara alamiah – akan berhadapan dengan kekuatan rakyat yang tak terkendali. Bagi rakyat sangat sederhana cara pandangnya: Jokowi gagal menciptakan kesejahteraan yang wajar seperti yang diamanatkan konstitusi, bahkan kian memperlebar jurang perbedaan kaya-miskin; gagal mendahulukan kepentingan pribumi dibanding asing, sehingga sumber daya alam kian terkesplorasi tanpa kendali, sehingga kedaulatan energi kian tercengkram kelestariannya. Juga, gagal menciptakan keadilan hukum dan politik. Catatan HAM juga buruk. Bahkan, gagal menciptakan tata-kelola pemerintahan yang reduktif terhadap panorama korupsi.
Panorama kegagalan itu semua akan menggerakkan berbagai elemen bangsa ini jika dipaksakan perpanjangan masa jabatannya menjadi tiga periode. Dasar pemikirannya sederhana: satu periode plus saja sudah menunjukkan kinerja yang penuh masalah bagi kepentingan bangsa dan negara, apalagi menambah tiga periode. Ada logika yang sangat mis (keliru). Namun demikian, atas nama politik pemaksaan kehendak, rezim bukan tak mungkin mengerahkan seluruh kekuatannya yang siap menghantam siapapun yang berseberangan.
Dalam hal ini, meski dengan kepentingan yang berbeda, tidak tertutup kemungkinan bahwa PDIP dan Gerindra akan tampil sebagai barisan lawan politiknya dengan sang penguasa. Dalam hal ini terdapat dua langkah yang dilakukan, yaitu saluran kebijakan: parlemen dan Mahkamah Konstitusi yang sama-sama bisa dikemdalikan oleh kedua parpol itu. Sisi lain, pengerahan kekuatan lapangan. Dalam hal ini aparat keamanan dari barisan TNI dan Polri – secara faktual – ada dalam genggaman kekuasaan kedua parpol itu, meski proses politik administratifnya diangkat Presiden. Dengan demikian, kedua jalur politik tersebut akan membuat loyo rezim jika tetap mengerahkan kekuatan paksanya.
Mencermati peta kekuatan politik yang berpotensi menghancurkan kepentingan bangsa dan negara, maka Partai Negeri Daulat Indonesia (PANDAI) – secara bijak – menegaskan bahwa pemaksaan kehendak sungguh merugikan kepentingan negara dan rakyatnya. Karena itu, di tengah krisis muktidimesional ini harusnya menjauhkan diri dari keinginan “mengotak-atik” amandemen, terutama terkait Pasal 7 UUD NRI 1945.
Pemimpin negara haruslah bijaksana bahwa pemaksaan kehendak memperpajang masa kekusaan hanyalah dinikmati oleh negara komprador yang jelas punya agenda strategis bagi negeri ini. Sangat a nasionalis. Sementara, sang presiden akan menjadi the common enemy bagi bangsanya sendiri, sehingga kelak tidak akan nyaman hidupnya pasca kekuasaannya berakhir.
Sumber : Farhat Abbas
Editor : Kurnia


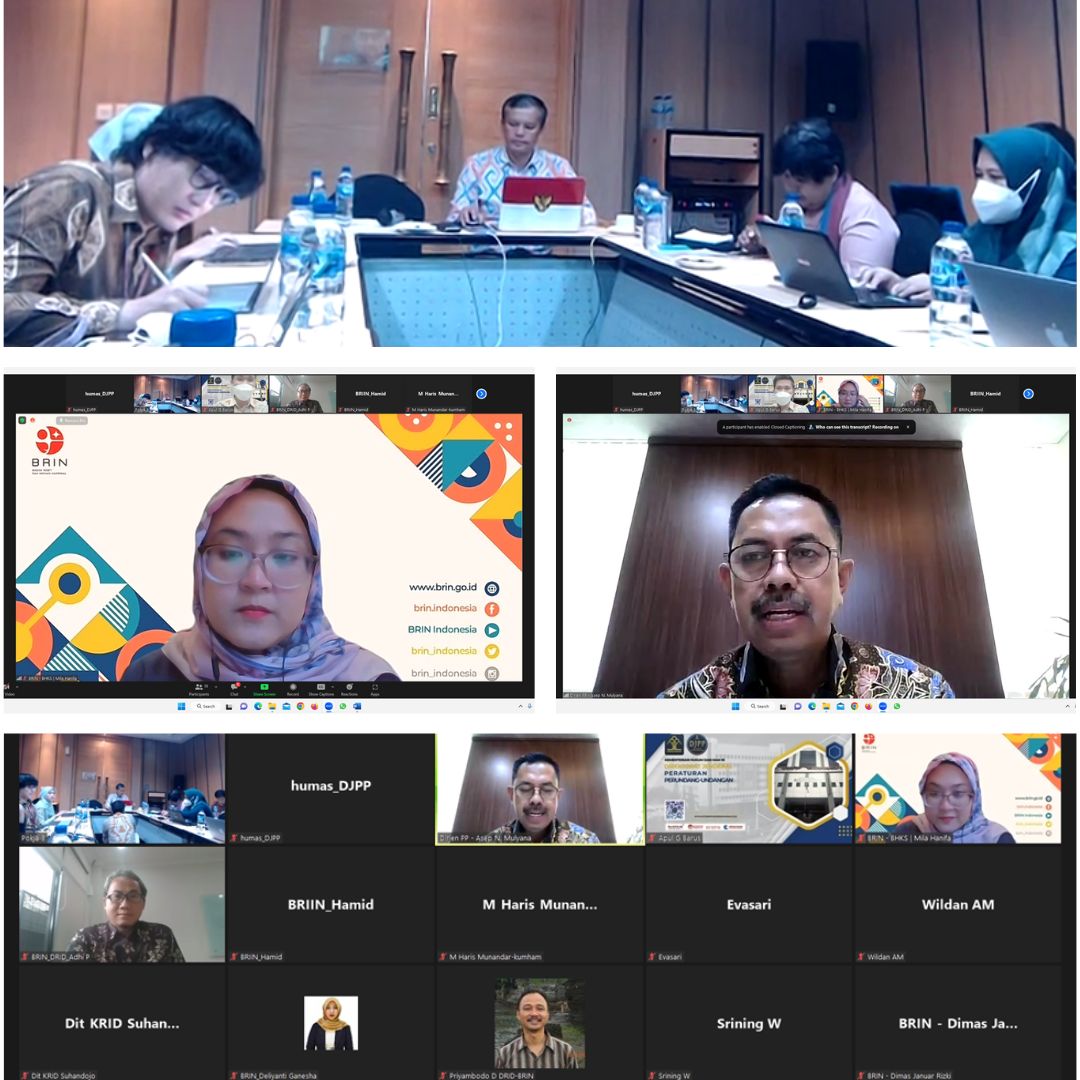














You must be logged in to post a comment Login